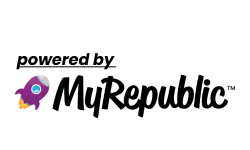Berikut tiga alasan utama mengapa merger kedua operator perlu diwujudkan.
Industri Selular Tengah Menurun
Berkat massifnya pembangunan jaringan 4G oleh operator selular, kini ekonomi digital berkembang sangat pesat di Indonesia.
Dalam catatan ATSI (Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia), lebih dari Rp 4.000 triliun ekonomi digital berputar di Indonesia saat ini.
Senada dengan ATSI, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa ekonomi digital Indonesia adalah yang tertinggi di Asia Tenggara.
Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai sekitar USD 70 miliar pada 2021. Jumlah itu terus meningkat, diperkirakan menembus USD 146 miliar pada 2025.
Ironisnya, industri selular yang menjadi penopang melejitnya ekonomi digital itu, malah sedang tidak sedang baik-baik saja.
Tercermin dari pertumbuhan yang kini menukik tajam, hanya berkisar 5% – 6% per tahun. Padahal dua dekade lalu, saat basic service (voice dan SMS) masih medominasi, pertumbuhan mampu mencapai double digit.
Baca Juga: Merger Dengan Smartfren, Bos XL Akui Akan Membawa Industri Lebih Sehat
Tingginya Regulatory Charges
Asosiasi Operator Selular Global (GSMA) menyebutkan komposisi rata-rata BHP terhadap pendapatan di Asia Pasifik mencapai 8,7%, sedangkan index global hanya sebesar 7%.
Sementara di Indonesia, regulatory charges yang dibayarkan operator kepada pemerintah, terutama dalam bentuk lisensi spectrum atau BHP (Biaya Hak Penggunaan) frekwensi sudah sangat tinggi, melebihi indeks global.
Dalam catatan ATSI, regulatory charges rata-rata berkontribusi 20% sampai 25% dari total biaya operasional (opex).
Otomatis beban BHP di Indonesia itu sudah mencekik leher operator. Sehingga sudah masuk pada fase tidak mendukung keberlanjutan industri.
Apalagi kenaikan BHP tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan operator. Secara compounded annual growth rate (CAGR) terbilang timpang.
Faktanya peningkatan pendapatan operator selular sepanjang periode 2013-2022 hanya tumbuh 5,69%. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tren peningkatan BHP frekuensi yang mencapai 12,1%.
Dengan kata lain, regulatory charges yang tinggi telah membebani keuangan operator dan berdampak pada kemampuan berinvestasi, serta kemampuan operasional.
Sejauh ini operator memang telah melakukan berbagai upaya dan efisiensi guna meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban operasional.
Itu sebabnya, melalui ATSI, operator telah meminta agar pemerintah bersedia mengurangi regulatory charges agar kesehatan industri bisa kembali pulih.
Namun tidak bisa dipungkiri, keputusan pemangkasan regulatory charges tidak semudah membalik telapak tangan. Dalam hal ini, Kominfo tidak bisa bertindak sendiri.
Karena bisa berdampak pada PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), perubahan kebijakan regulatory charges terutama BHP frekwensi, perlu melibatkan stake holder lain, seperti Kementerian Keuangan dan BPK.
Baca Juga: XL Axiata Kembali Tanggapi Soal Merger dengan Smartfren

Tarif Rendah Menghambat Perluasan Jaringan Ke Daerah
Selama ini dipersepsikan bahwa tarif internet di Indonesia terbilang mahal. Faktanya, tarif data yang dipatok operator selular adalah salah satu yang tergolong murah di dunia.
Dilansir dari cable.co.uk (14/10/2020), sebuah survei teknologi yang berbasis di Inggris, terungkap bahwa Indonesia menempati urutan ke-14 sebagai negara dengan tarif data selular murah per 1GB dari 228 negara yang disurvei.
Rata-rata biaya 1GB data selular di Indonesia adalah Rp 9.440. Tarif itu, lebih murah dibandingkan dengan Myanmar (Rp 11.505), Malaysia Rp (16.520), Thailand (Rp 18.142) dan Filipina (Rp 20.945). Sedangkan tarif termurah di kawasan Asia Tenggara ditempati Vietnam sebesar Rp 8.408.
Tarif murah, tentu menguntungkan konsumen. Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah atau kota yang sudah terbangun jaringan broadband.
Namun dalam jangka panjang, harga layanan internet yang terlalu murah, justru berdampak pada stabilitas bisnis operator telekomunikasi karena kesulitan menggelar jaringan ke daerah.
Sesuai dengan lisensi nasional yang dimiliki, operator dituntut untuk terus memperluas jaringan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Namun perluasan itu sulit dicapai jika pendapatan yang diperoleh kecil akibat perang tarif atau tarif murah.
Saat ini operator masih terus melakukan pemerataan jaringan hingga ke pelosok negeri. Pada saat yang bersamaan, operator juga harus meningkatkan jaringan ke teknologi yang lebih baru, seperti 5G di tengah pembangunan jaringan 4G yang masih berjalan.
Padahal untuk menggelar jaringan 5G, investasi yang dikeluarkan operator terbilang sangat besar. Kajian Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) mengungkapkan, biaya penggelaran jaringan 5G, sekitar 30% lebih mahal dibandingkan 4G.
Dengan biaya yang sangat besar, sementara use case dan ekosistem 5G belum terbentuk, wajar jika operator berhati-hati dalam membangun jaringan 5G, meski layanan ini sudah diperkenalkan di Indonesia sejak 2021 silam.
Baca Juga: Jika Terjadi Merger XL Axiata dan Smartfren, Penguasaan Frekwensi Nyaris Menyamai Telkomsel