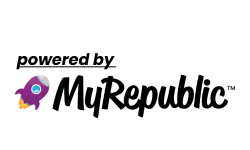“Kok, rasa-rasanya wajah saya mirip dengan Prabowo ya?”
Kalimat itu meluncur dari Rudiantara, sesaat setelah kami selfie bersama. Saya yang sebelumnya sudah cukup senang bisa berfoto bersama dengan Pak Menteri, mendadak jadi lebih fokus memperhatikan wajah sang Menkominfo. Setelah dipelototi, setengah tidak percaya, ternyata ada kemiripan di antara keduanya.
“Wah, benar, nggak nyangka Bapak mirip Prabowo. Nggak percuma dipanggil chief. Bisa masuk ke ASAL juga nih”, ujar saya menimpali, merujuk pada acara yang menampilkan tokoh asli dan palsu di salah satu stasiun TV swasta. Seketika, kami pun tertawa lepas, membuat pertemuan sore ini cukup berkesan.
Itulah akhir dari sesi wawancara ekslusif tim redaksi Selular Media Group (SMG) dengan Rudiantara, di ruang kerjanya di Jakarta, Jumat (13/2/2014). Wawancara yang lebih mirip dengan diskusi santai ini membahas panjang lebar permasalahan industri ICT (Information & Communication Technology) di Indonesia dan solusi yang kini tengah digenjot oleh Kemenkominfo.
Salah satu topik yang menjadi perhatian kami adalah isu tentang kewajiban pabrikan ponsel untuk membangun pabrik di Indonesia. Beleid itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet.
Praktis sejak akhir 2014, isu ini memang menjadi bola panas yang membuat para pemain terutama para vendor ponsel kebakaran jenggot. Khususnya mereka yang sama sekali tidak memiliki road map membangun pabrik, alias hanya menjadikan Indonesia sebagai basis pasar semata.
Beleid itu memang tidak main-main. Pasalnya, untuk memperkuat efektifitas di lapangan, Kemendag didukung penuh oleh dua kementerian masing-masing Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perindustrian. Ketiganya sepakat untuk menetapkan kebijakan sinergis soal tingkat kandungan lokal dalam negeri (TKDN) untuk semua ponsel 4G yang masuk ke Indonesia mulai 1 Januari 2017 nanti.
”Kalau kurang dari 40%, Kementerian Perdagangan nggak akan kasih izin. Vendor-vendor besar seperti Samsung atau iPhone mau nggak mau juga harus. Kalau nggak ya nggak kita izinin. Ini berlaku untuk semua vendor tanpa terkecuali,” tegas Chief RA, panggilan akrab menteri urusan ICT ini.
Rudiantara menjelaskan bahwa ketentuan tentang pembangunan pabrik tidak keluar ujug-ujug, apalagi dinilai memiliki agenda tersembunyi. Sebagai menteri berlatar profesional, ia menjelaskan bahwa Indonesia selama ini merupakan surga bagi para vendor ponsel terutama merek-merek global.
Sayangnya, sejak pasar ponsel mulai bergeliat di era analog 25 tahun lalu, kemudian berkembang ke voice dan SMS, dan kini memasuki layanan data berbasis broadband (4G LTE), nyatanya tak satu pun vendor ponsel asing yang membangun pabrik ponsel di Tanah Air.
Pemain-pemain besar termasuk para penguasa pasar, silih berganti. Dari Motorola, Ericsson, Siemens, Nokia, Blackberry, dan hingga kini Samsung, hanya sekedar menjadikan Indonesia tak lebih dari sekadar basis pasar yang menggiurkan tanpa berniat menanamkan investasi di sisi manufaktur.
Tengok saja perlakuan Nokia. Selama lebih dari satu dekade (1999 – 2007) menjadi market leader di pasar domestik, tentu sudah ratusan triliun rupiah mereka angkut ke Finlandia. Tapi karena tidak ada peraturan yang memaksa mereka membangun pabrik atau transfer teknologi, kita tak melihat legacy yang ditinggalkan selain kantor di Menara Mulya, Gatot Subroto (Jakarta).
Yang lebih menyakitkan, dalam masa kejayaannya, Nokia bahkan lebih memilih Singapura sebagai kantor regional. Mereka menjadikan Jakarta tak lebih dari kantor perwakilan. Nokia juga lebih memilih membangun pabrik di Malaysia ketimbang Indonesia. Kini ditangan pemilik baru, Microsoft, Nokia berusaha merintis kembali kedigdayaan yang pernah dikuasai. Namun hingga peralihan kepemilikan, tak ada rencana Microsoft untuk membangun pabrik Nokia di sini.
Menyikapi hal ini, wajar jika pemerintahan baru bergerak cepat dan mengambil kebijakan yang diharapkan kelak akan menguntungkan Indonesia dalam jangka menengah dan panjang. Apalagi sebagai emerging country, Indonesia sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan China dan India. Belajar dari kebijakan masa lalu yang cenderung memanjakan para vendor asing, kita selayaknya tak harus malu belajar dari kesalahan.
Seperti diketahui, dua dekade lalu, Indonesia tak berbeda dengan India dan China. Hanya dijadikan basis pasar oleh vendor-vendor asing karena populasi yang gede. Namun lewat kebijakan yang konsisten dan terarah, dua negara besar itu pada akhirnya mampu naik kelas, dari sekedar pasar menjadi produsen.
Di India, produsen ponsel lokal kini mulai merajai. Salah satunya Micromax yang sukses mengungguli Samsung. Begitu pun dengan China. Siapa tak kenal dengan Oppo, Haier, Hisense, ZTE atau Huawei? Sejak lima tahun terakhir, deretan ponsel China begitu dashyat menyerbu pasar global, termasuk Indonesia.
Bahkan, kalau kita mau jujur, ponsel-ponsel yang merupakan produk lokal, seperti Evercoss, Mito, Advan, V-Gen, Asiafone dan lainnya, sesungguhnya jeroan dan casing-nya masih diproduksi di China daratan. Setelah dilabeli, baru dipasarkan di Indonesia.
Ironisnya karena terlalu liberal, nilai importasi ponsel terus membengkak.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pertumbuhan pasar ponsel Indonesia mencapai 15 persen per tahun. Pada 2012, impor ponsel secara nasional mencapai 53 juta unit atau senilai US$ 2,6 miliar. Setahun berikutnya, yakni 2013 impor meningkat menjadi 58 juta unit atau US$ 2,9 miliar. Hingga Agustus 2014 nilai impor sudah mencapai 34 juta unit, setara dengan US$ 2,1 miliar, dengan perkiraan bisa menembus US$ 4 miliar.
Namun, defisit perdagangan bukan cuma dari impor ponsel, tetapi juga dari konten dan aplikasi yang menyertai. Nilai konten aplikasi di smartphone yang mengalir ke luar negeri pun tidak tanggung-tanggung, mencapai Rp 70 triliun.
Soal konten dan aplikasi ini yang juga menjadi concern Rudiantara. Sebab sektor ICT adalah contoh nyata di mana nilai software lebih tinggi dari pada nilai hardware.
“Itu mau kami tangkap juga. Karya-karya anak bangsa kan, banyak yang bagus dan punya nilai jual di pasar global. Nah, mereka medianya kan smartphone, harus dibuat juga ketentuan memasukkan konten lokal.”, ujar Rudiantara.
Alhasil, kini penghitungan nilai TKDN tidak hanya memuat aspek manufaktur produk melainkan pula pengembangan dan desain termasuk di dalamnya. Bobot nilai konten lokal dari aspek pengembangan produk sebesar 20%, sedangkan TKDN manufaktur 80%.
Dengan aturan ini, Rudiantara berharap ke depan, industri ponsel di Indonesia akan semakin bergairah sekaligus mandiri. Tak hanya dari sisi manufaktur tapi juga aplikasi yang merupakan produk unggulan dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat di era mobile life style.
Bagi Rudiantara, kewajiban pabrikasi bagi produsen ponsel sekaligus menandai 100 hari pencapaian Kemenkominfo. Dia kembali menegaskan bahwa tanpa kebijakan TKDN sama saja dengan membiarkan defisit neraca perdagangan minimal USD 3 miliar setiap tahun.
Rudiantara mengakui, bagi vendor global kebijakan ini mungkin tidak popular. Tapi ia bertekad akan terus jalan demi perbaikan industri telekomunikasi supaya Indonesia tidak terus tercecer dalam persaingan global.
“Saya nothing to loose aja. Toh, saya tak punya kepentingan apa-apa, apalagi kepentingan politik”, pungkasnya.
Oke, chief maju terus… !